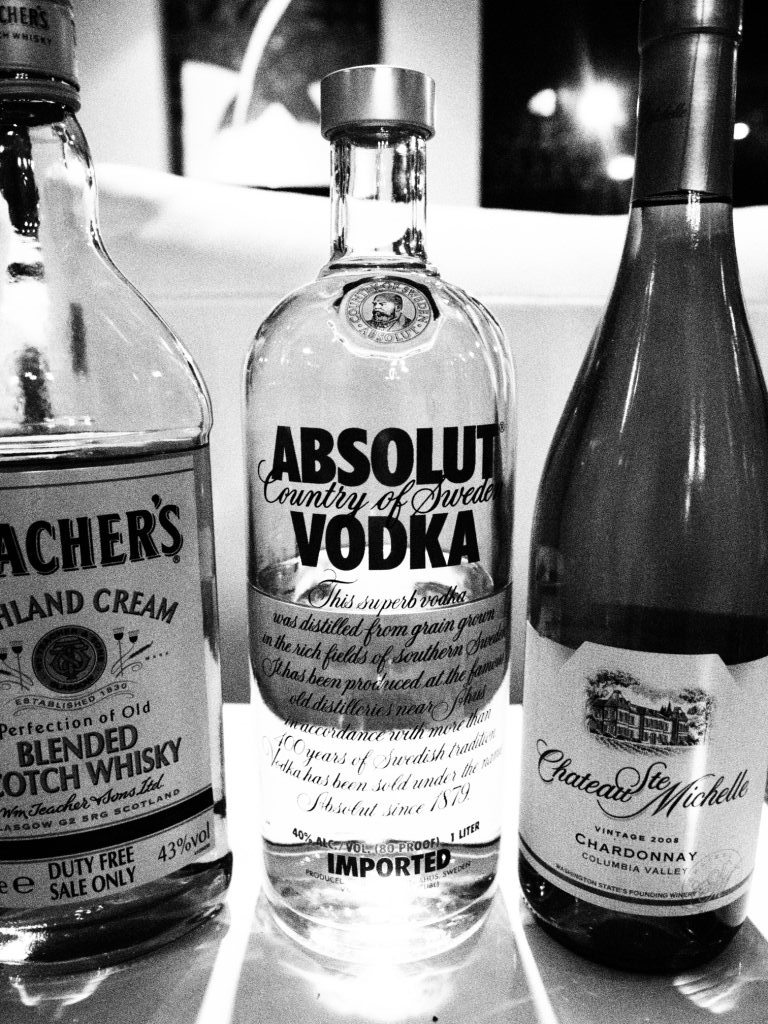…tidak inklusi…
Bagi yang sering menggunakan angkutan umum atau mencari ruang memarkirkan mobilnya di Jakarta pasti tahu bahwa ada pengkhususan bagi perempuan. Memang, kaum perempuan senang dengan adanya pengistimewaan ini. Tapi tahukah kamu, bahwa kondisi ini makin memperjelas bahwa negeri ini tidak inklusi?
Di satu sisi, perempuan meminta haknya untuk disetarakan dengan kaum pria, tetapi di sisi lain, dengan adanya pembedaan itu, menyatakan bahwa perempuan itu minta dibedakan?
Terus terang, saya juga beberapa kali menggunakan lahan parkir untuk perempuan karena memang sedang kosong. Tapi ada kejadian yang sampai sekarang tidak pernah akan dilupakan ketika saya hendak parkir di mal besar di dekat Tugu Selamat Datang. Saat itu, saya ancang-ancang parkir mundur dan si petugas parkir mengatakan, “Saya bantu parkirkan saja, mbak.” Berhubung saya sedang fokus dengan mobil, saya tidak begitu peduli dengan tawarannya. Tapi setelah saya reka ulang, saya berkesimpulan bahwa yang ia baru saja lakukan adalah suatu penghinaan dan merendahkan martabat. Begitu banyak contoh yang kalau ditulis bisa menjadi sangat panjang.
Tidaklah heran ketika banyak kaum pria yang kemudian merendahkan bahkan melecehkan perempuan. Seharusnya yang diperbaiki adalah pola pikir, bukan malah memperuncing minta perlakuan khusus.
– di gerbong kereta campur –
..bahasa persatuan..
Mumpung waktunya tepat, walau lagi ada dokumen yang harus diterjemahkan, gue tetap mau meluangkan waktu untuk menulis tentang pengalaman saat gue di Jerman, tepatnya waktu di Stuttgart.
Ada tiga kejadian di tempat dan hari berbeda dengan satu benang merah yang sama, yaitu ketika gue jalan-jalan ke objek wisata mereka. Yang pertama, saat gue ke Solitude Palace. Demi ingin tahu apa yang ada di dalam Istana, dan gue hanya bisa masuk kalau ikut tur yang dipandu mereka, jadilah gue mendaftar untuk tur mereka. Tapi mau tahu? Mereka tidak punya tur berbahasa Inggris, yang menurut gue bahasa pemersatu di dunia ini. Mereka hanya punya tur berbahasa Jerman. Berhubung gue mau tahu isinya (dan mau motret juga), ya gue tetap ikuti itu tur. Mulai dari menit pertama hingga menit terakhir, ketika pengunjung lain tergelak, gue benar-benar bagai di alam lain, nggak tahu apa yang dijelaskan. Dan, gue nggak bisa motret!
Kejadian kedua, ketika gue ke Ludwigsburg Palace. Sebelum ke sini, gue cek dulu, apakah mereka punya tur berbahasa Inggris, karena seperti Solitude, hanya pengunjung yang membayar yang bisa masuk ke dalam Istana, selebihnya hanya di pelataran istana, dan itu gratis. Waktu mau bayar tiket masuk, gue tanya ke kasirnya, jam berapa tur berikutnya. Dan mau tahu? Dia bilang tur berbahasa Inggris berikutnya sudah penuh dan yang tersisa yang berbahasa Jerman. Kalau tetap mau yang berbahasa Inggris, gue harus menunggu 1 jam lagi, sementara di seputaran istana tidak ada objek wisata lainnya. Sial… Akhirnya gue tetap bayar dan ikut tur berbahasa Jerman itu. Dan sekali lagi, setelah di dalam, baru gue tahu kalau gue nggak bisa motret!
Kejadian ketiga ini sebenarnya banyak gue alami di museum-museum di Jerman, jadi bukan hanya di Stuttgart. Banyak sekali keterangan untuk peraga tidak ada dalam bahasa Inggris, jadi gue hanya lihat gambar sambil sekali-kali lihat Google Translate (asli lelah dan menghabiskan banyak waktu!).
Waktu gue mengalami kejadian ini, gue langsung ingat sama orang-orang yang melecehkan Jokowi yang “menurut mereka si kaum penyebar fitnah”, tidak bisa bahasa Inggris dan mereka tidak sudi dipimpin oleh orang yang bahasa Inggrisnya kacau. Mereka juga bilang, bagaimana Indonesia mau maju kalau Presidennya tidak bisa bahasa Inggris?
Yang gue mau tulis di sini, bahwa kenapa sih, kita, yang jelas-jelas rakyat Indonesia, bahasa persatuannya adalah Bahasa Indonesia, malu untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia? Apa karena kita selalu menggunakan Bahasa Indonesia lalu kita tidak akan bisa menjadi negara maju? Jerman adalah bukti nyata bahwa warganya tidak semua bisa bahasa Inggris, keterangan untuk para wisatawan dalam bahasa mereka, tapi itu tidak menghalangi wisatawan untuk pergi ke sana. Jerman adalah negara maju, dan salah satu negara kaya yang mengucurkan banya dana untuk membantu negara di benua Eropa lainnya yang terpuruk akan krisis!
Salah satu isi dari ikrar Sumpah Pemuda, tepatnya di kalimat terakhir, “…Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia”. Jadi sudah jelas, bahwa bahasa kita itu bahasa Indonesia. Pernah nggak kalian menyadari, bahwa begitu banyak buku pelajaran Bahasa Inggris tapi buku tentang Bahasa Indonesia bisa dihitung dengan jari? Pernah tidak kalian melihat sekeliling, betapa banyak bertebaran kalimat atau jargon dalam bahasa Inggris tapi jarang yang memakai Bahasa Indonesia? Pernah tidak kalian berpikir bahwa kalian lebih bangga jika anak kalian menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia? Kalian, para orangtua, saling membanggakan bahwa anaknya sudah bisa bahasa Mandarin atau Inggris, lalu ketika anaknya bertanya mengenai arti suatu kata yang umum digunakan dalam Bahasa Indonesia, kalian hanya tertawa? Tidakkah kalian berpikir bahwa kalian berkontribusi untuk menghilangkan bahasa pemersatu negeri ini secara perlahan? Kita masih terjebak dalam stigma, bahwa dengan berkomunikasi dalam Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, maka kita akan terlihat keren.
Maaf, tapi buat gue, orang yang keren itu adalah orang yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, yang membuat gue terperangah ketika mendengar orang tersebut bisa membedakan kapan mengucapkan “kami” dan “kita”. Ya, Bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya memang penting, tapi bukan berarti kita lalu bisa seenaknya saja bergegas meninggalkan pemakaian Bahasa Indonesia. Ada kalanya bahasa asing diperlukan, tapi jangan sampai kalian melupakan bahasa negeri sendiri.
Gue sering bertukar pikiran sama ibu gue, membayangkan masa depan bahasa Indonesia. Menurut kami, kalau rakyat Indonesia masih tetap seperti ini, dan bahkan bisa lebih parah lagi, maka tidak heran kalau dalam waktu 10 tahun ke depan, bahasa Indonesia akan punah dan masuk ke daftar bahasa langka yang dikeluarkan PBB. Tidak usah membicarakan bahasa daerah yang nasibnya lebih buruk (terutama bahasa Jawa, karena penggunanya kalau sudah pindah ke Jakarta terus langsung hilang ingatan akan bahasa yang dimiliki dari kecil).
Gue berharap, prediksi gue akan punahnya Bahasa Indonesia tidak terjadi, tapi gejala ke sana sudah mulai terjadi dari sekarang. Cukup miris melihat begitu banyak teman yang pandai menulis dalam Bahasa Inggris, tetapi ketika menulis dalam Bahasa Indonesia, tidak bisa membedakan penulisan ‘di’ yang dipisah dan disambung. Sederhana tapi menjengkelkan, karena itu adalah hal yang sangat mendasar. Cukup miris ketika mereka berlomba-lomba untuk mengambil ujian TOEFL tapi bahkan tidak pernah mendengar kalau kita punya yang namanya UKBI (Ujian Kompetensi Bahasa Indonesia).
Belum terlambat untuk mengubah nasib bahasa persatuan kita. Kalau kalian cinta akan negeri ini, cinta akan bahasa kita, menghargai jasa mereka yang telah bersusah-payah mengucap ikrar pada tanggal 28 Oktober 1928, gue mengajak kalian untuk mulai lebih sering menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi? Masak nunggu orang asing untuk menyelamatkannya seperti yang sudah terjadi dengan kesenian-kesenian kita?
*kembali bekerja*